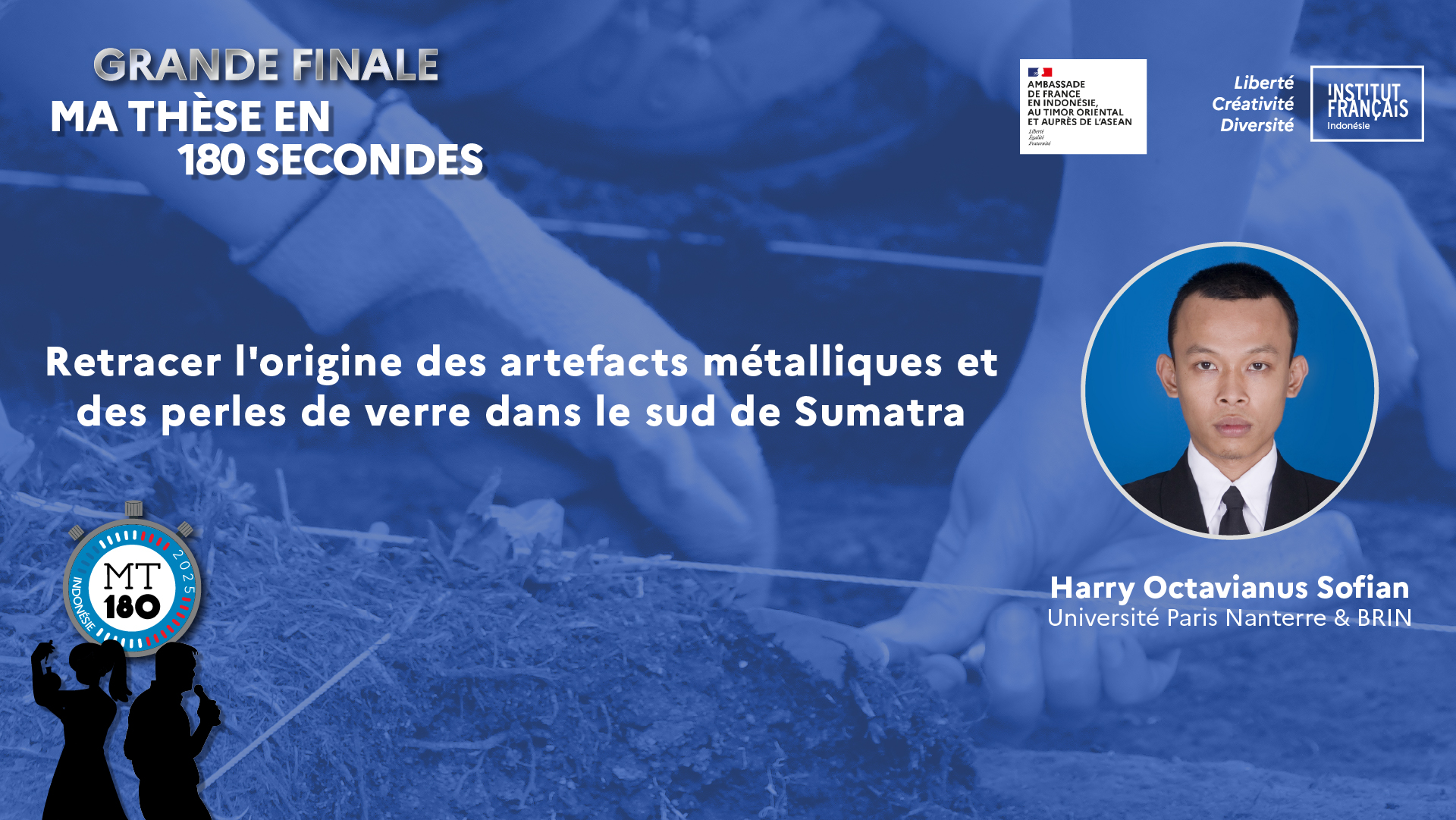
Nama saya Harry Sofian, saya seorang arkeolog.
Disertasi saya tentang sejarah perdagangan logam dan manik-manik kaca di selatan Sumatra sungai Musi dan Batanghari, serta pegunungan Bukit Barisan. Lanskap geografis Musi dan Batanghari unik karena terdapat desa-desa pesisir kuno, pusat-pusat Hindu dan Buddha. Namun, di pegunungan Bukit Barisan terdapat tradisi megalitik di mana penduduk menggunakan batu-batu besar untuk upacara keagamaan.
Penelitian saya bertujuan untuk mengeksplorasi pertukaran benda-benda mineral dan teknologi antara budaya megalitik dan Hindu-Buddha. Saya menganalisis sekitar tiga puluh logam dan dua ratus manik-manik kaca. Hasilnya menunjukkan bahwa logam-logam tersebut merupakan produk lokal Sumatra. Namun, manik-manik kaca diimpor dari India, Mesopotamia, dan Mesir.
Kesimpulannya, jelas bahwa terdapat perdagangan antar kawasan yang luas Hal ini telah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu di Asia Tenggara. Artinya, manusia telah bergantung pada sumber daya mineral sejak lama. Dan sekarang, apakah kita bisa hidup tanpa logam atau manik-manik kaca?
Andalah yang dapat menjawabnya.
Terima kasih banyak atas perhatian Anda.
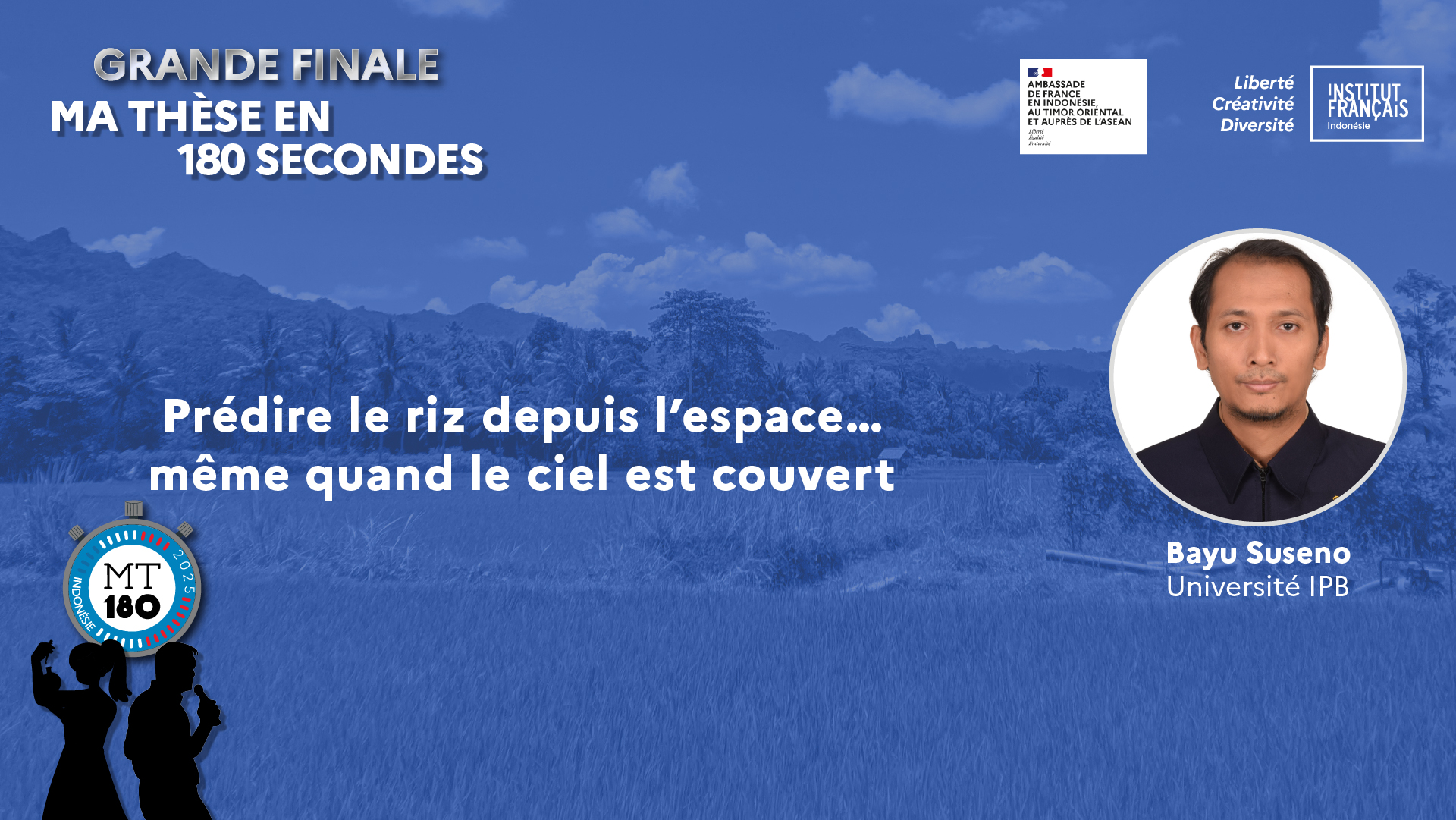
Halo semuanya.
Nama saya Bayu dan saya orang Indonesia.
Bagaimana menjadi orang Indonesia ? Mudah, makan nasi setiap hari. Makan tanpa nasi bukan
benar-benar makan bagi kami ! Sampai dengan 2025, beras tetap menjadi makanan pokok di Indonesia.
Pemerintah melakukan banyak program untuk menjamin ketersediaan beras dan meningkatkan
kesejahteraan petani. Pemerintah memantau sawah-sawah menggunakan survei lapangan. Metode ini presisi namun mahal untuk dilakukan pada wilayah yang luas seperti Indonesia. Apakah ada alternatif lain ? Ya, satelit ! Satelit bisa mengamati lahan pertanian di mana saja secara teratur dan bahkan gratis. Tapi ada sebuah masalah : Awan ! Di Indonesia, pada musim penghujan terdapat banyak awan yang bisa menghalangi pandangan satelit.
Lalu apa yang bisa dilakukan ? Apakah kita membutuhkan bantuan Rara, seorang pawang hujan untuk mengusir awan seperti saat MotoGP di Mandalika tahun 2022 ?
Tentu saja TIDAK !
Dalam penelitian saya, saya menemukan sebuah metode yang lebih masuk akal : MRTS-Boosting. Metode ini menggunakan data satelit untuk memantau sawah-sawah dengan lebih presisi meskipun pada saat musim penghujan.
Sebagai Kesimpulan, dengan MRTS-Boosting, pemerintah bisa memantau sawah-sawah dengan lebih presisi namun murah, dan …. Tanpa perlu memanggil Rara !
Terimakasih banyak atas perhatian Anda !
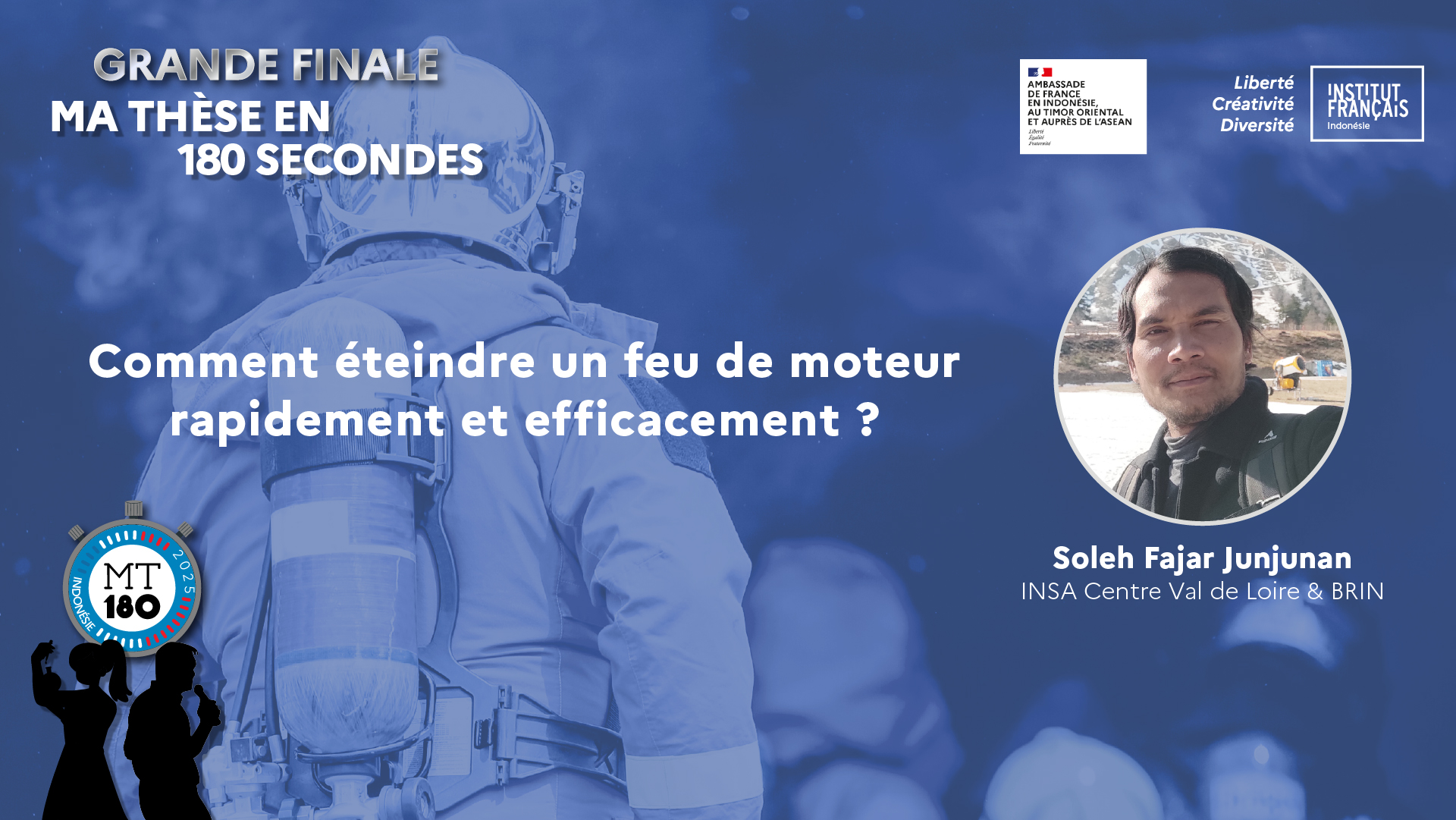
Halo semuanya!
Bayangkan sebuah truk besar berisi pasir Merapi, atau bus penuh penumpang, sedang melaju di jalan tol. Dan boom! Tiba-tiba, asap keluar dari kap mesin.
Itu api!
Panik!
Kebakaran ini sangat berbahaya bagi semua orang di dalam atau di luar kendaraan.
Sejak lama, untuk memadamkan api jenis ini, terutama pada kendaraan militer, orang-orang menggunakan gas: Halon. Masalahnya, gas ini merusak lapisan ozon. Jadi, bagaimana cara menemukan solusi yang efektif dan ramah lingkungan? Di sinilah disertasi saya berperan.
Saya mempelajari sistem yang disebut water mist. Sederhananya, ini adalah air yang diubah menjadi ribuan tetesan kecil, hampir seperti kabut. Tetesan ini memiliki kekuatan super: memadamkan api dengan menyerap panas dan mengurangi oksigen di sekitar api.
Selain itu, itu air… jadi bagus untuk lingkungan!
Untuk menguji semua ini, saya membuat ulang kebakaran nyata pada mesin kendaraan besar, tentu saja dengan aman! Kemudian saya menyemprotkan kabut air untuk melihat bagaimana
reaksinya berdasarkan beberapa parameter: tekanan air, penambahan aditif, termasuk
pengaruh ventilasi.
Hasilnya? Sangat baik!
Kabut air berhasil memadamkan api yang disebabkan oleh bensin atau oli, asalkan tekanan airnya sesuai. Aditif juga dapat meningkatkan efektivitasnya, jadi layak untuk dieksplorasi.
Singkatnya, disertasi saya mengusulkan solusi otomatis, efektif, ramah lingkungan, dan lebih aman untuk memadamkan kebakaran pada kendaraan besar. Berkat teknologi ini, truk, bus, dan bahkan kendaraan militer di masa depan akan dapat melindungi diri dari kebakaran dan melindungi penumpang… juga planet ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya!
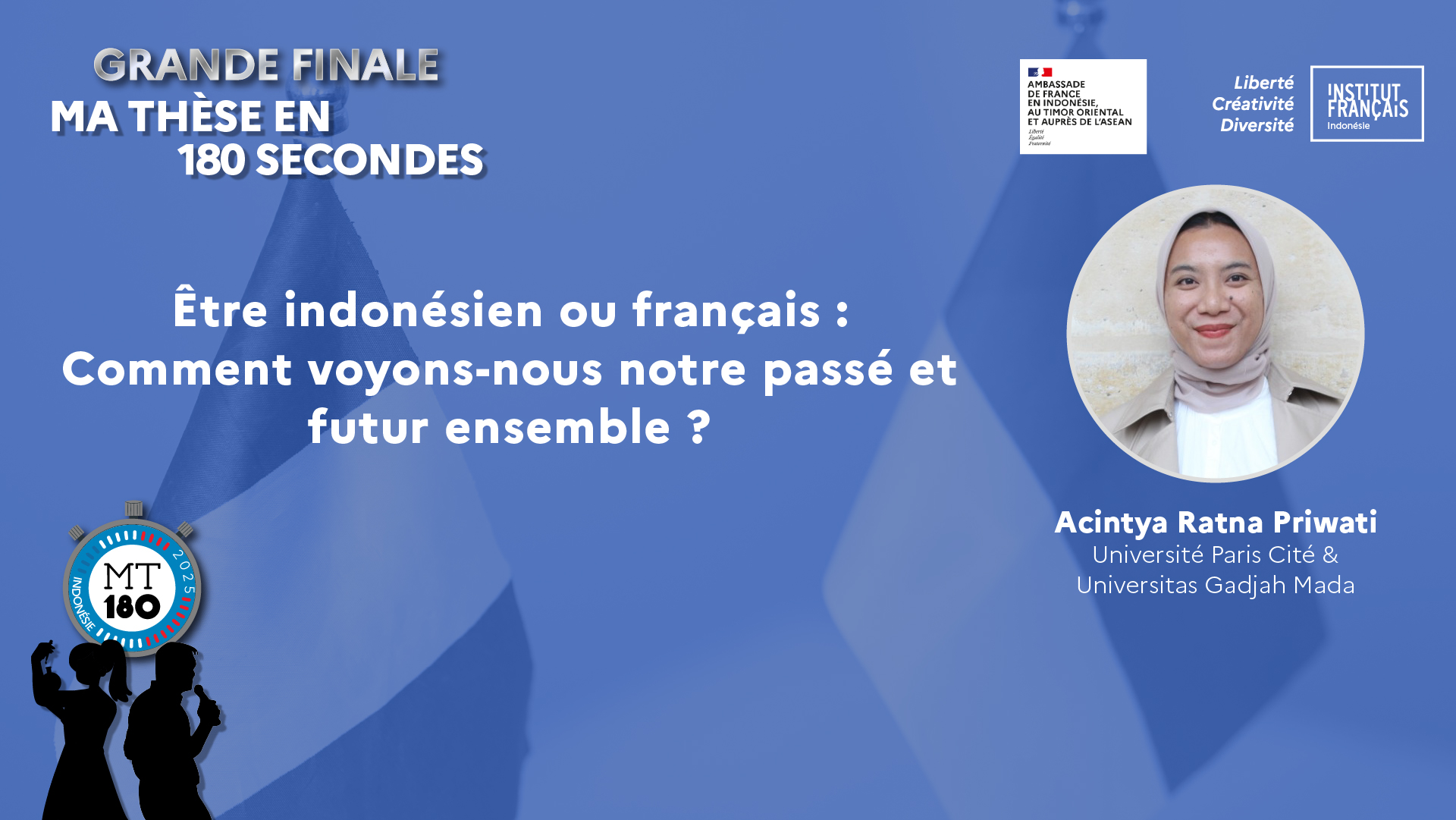
Acintya memiliki dua orang sahabat, Julia dari Indonesia dan Julie dari Prancis. Sebuah pertanyaan sederhana melintas di pikirannya, apa arti menjadi orang Indonesia atau orang Prancis? Apakah terkait tempat lahir, keluarga, maupun bahasa?
Di negara Barat seperti Prancis, pertanyaan ini sering diajukan, namun jarang di Indonesia. Untuk menjawabnya, ia menggali pertanyaan kepada lebih dari 1800 orang Indonesia dan lebih dari 700 orang Prancis. Pertanyaan yang diajukan meliputi arti menjadi orang Indonesia atau orang Prancis, peristiwa negara yang dianggap paling berkesan, dan pandangan mereka tentang masa depan negara.
Hasil menunjukkan bahwa orang Indonesia banyak membicarakan mengenai keluarga, asal usul, dan rasa bangga pada masa lalu negara, serta lebih positif mengenai masa depan negara. Jika diilustrasikan, ada “garis” yang naik dari masa lalu ke masa depan. Sementara orang Prancis menunjukkan “garis” yang sedikit menurun. Mereka lebih focus pada nilai-nilai, hukum, dan cenderung lebih khawatir mengenai masa depan
negaranya.
Kesimpulannya, cara kita memandang masa lalu dan masa depan negara dipengaruhi oleh budaya. Di Indonesia, kehidupan personal dan sosial bercampur (kecenderungan kolektivis) sementara di Prancis keduanya dipisahkan (kecenderungan individualis). Setiap negara memiliki latar belakang budayanya masing-masing, dan dengan mengenalinya, dapat membantu kita untuk memahami satu sama lain dengan lebih
baik.
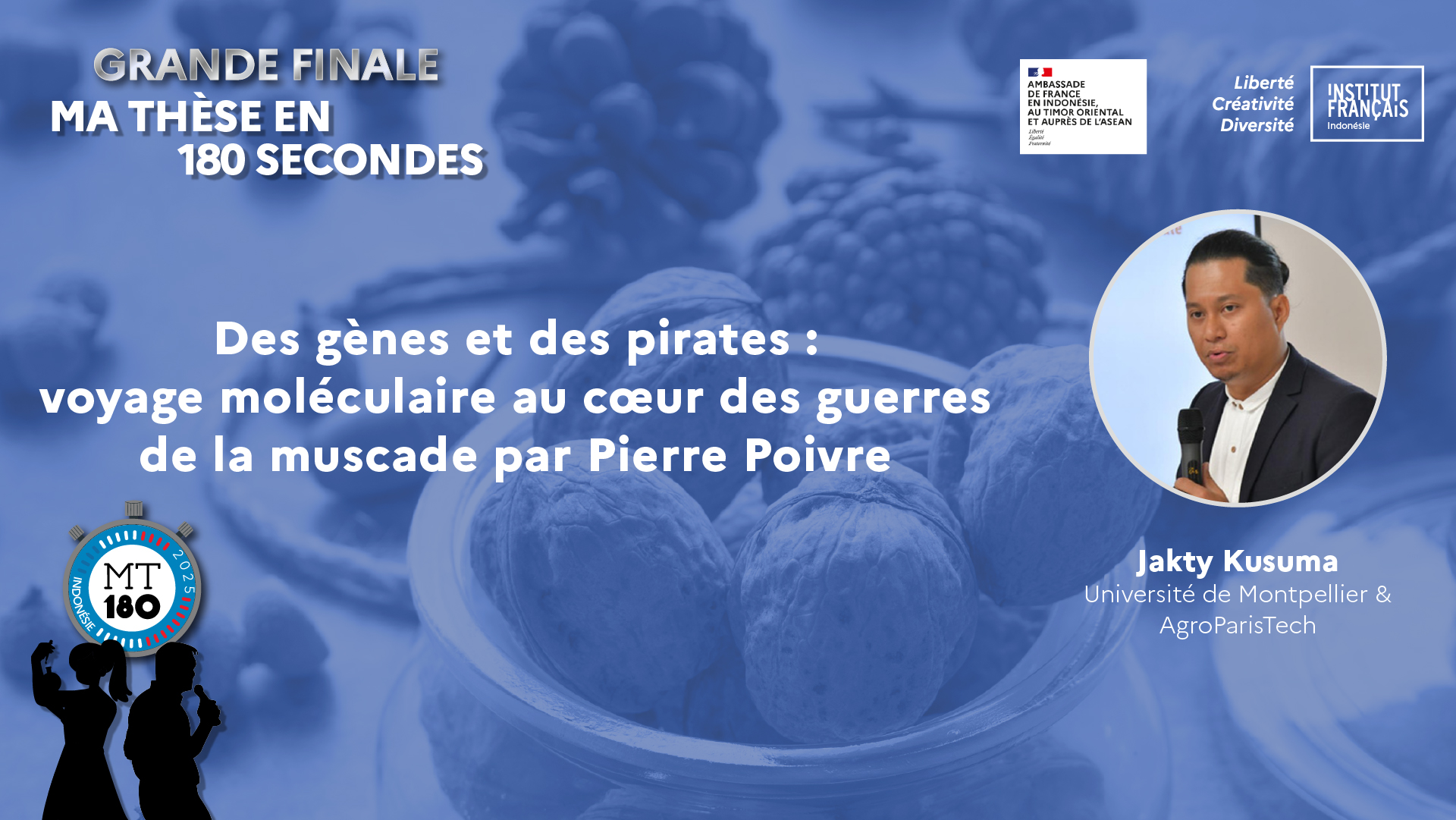
Dulu, di pulau-pulau jauh Maluku, ada pohon kecil yang tenang namanya pala. Si pala ini nggak nyangka bakal jadi pusat dari kisah soal kekuasaan dan perdagangan yang heboh. Buah pala dulu termasuk rempah paling mahal: dipakai untuk obat, dan tentu saja buat bumbu supaya masakan makin harum.
Karena itu, Eropa berdatangan ke Maluku. Tujuan mereka jelas: kuasai perdagangan pala. Orang Belanda, lewat VOC-nya, menganggap pala itu seperti “debu emas”. Mereka mau monopoli total. Semua serba dikontrol supaya harga dan suplai tetap milik mereka.
Lalu muncul satu tokoh unik: Pierre Poivre, orang Prancis, sekaligus misionaris, tukang kebun, dan sedikit nekat macam pelaut bajak laut. Tujuan dia: memecah monopoli Belanda. Caranya? Nyuri (eh, menyelundupkan) biji pala, simpan di kantong kain, dan bawa jauh-jauh, dari Indonesia sampai Réunion. Intinya: dia bawa pala keluar dari cengkraman VOC.
Dalam tesis ini aku pakai alat molekuler untuk melacak asal usul pala. Hasilnya? Semua pala yang sekarang tersebar di dunia, dari Karibia sampai Madagaskar, secara genetik ternyata berasal dari Maluku Selatan. Jadi, hipotesisnya benar: sumber utama penyebaran pala global itu memang dari situ. Dan ya, bukti genetiknya cocok banget sama cerita sejarah, yang mana Pierre Poivre memang dapat bijinya dari Maluku Selatan.
Antara petualangan dan ilmu, kisah ini menghargai lelaki yang, dengan tas kain di pundak dan sedikit keberanian, berhasil mengubah nasib sebuah pohon… dan mungkin sedikit mengubah jalannya sejarah perdagangan rempah.
Jadi… bangga atau nyesel? 😉
Saya Jakty — terima kasih atas perhatiannya

